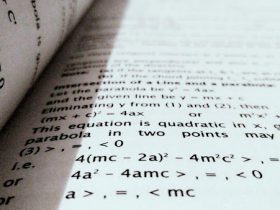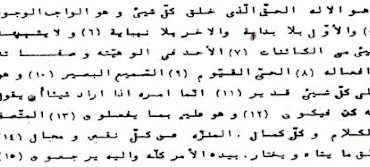SEJARAH PERKEMBANGAN TASAWUF
Kehidupan spiritual sejatinya merupakan fase dimana manusia berotasi pada eksistensi dirinya, dimana fokus utama terletak pada dimensi spiritualnya dan nafs, ruh, qalb adalah sasaran dari kontemplasi tersebut,1 yang lebih dikenal dengan asketisme.2 Jika diruntun lebih jauh lagi, bahwa kehidupan asketis tidak dapat dipisahkan dari literatur dalam tradisi Islam, dimana dapat dijumpai sejumlah dalil-dalil dalam al-Qur’an maupun Hadits3 yang menegaskan potensi manusia terutama dimensi spiritual yang mampu meninggalkan belenggu jasmani (nasitiyah) untuk menanjak naik melalui potensi lahitiyahnya. Inilah yang menjadikan perbincangan seputar teori dan konsep yang lahir berikutnya menjadi unik dan beragam.4
Sebagai salah satu dimensi keagamaan yang muncul di tengah agama dan peradaban lainnya, sufisme dalam Islam juga tidak luput dari keterpengaruhan tersebut. Mulai konsep-konsep ketuhanan Neo-Platonisme Yunani sampai tradisi gnostik dan asketik yang berkembang di agama-agama Yahudi, Nasrani, Zoroaster, Hindu dan sebagainya, kemudian dengan dominasi warna Islamlah Sufisme berkembang.5 Sufisme Awal
Sejak dekade akhir abad II Hijriah, sufisme sudah popular di kalangan masyarakat di kawasan dunia Islam, sebagai perkembangan lanjutan dari gaya keberagaman para zahid dan ‘abid, kesalehan yang mengelompok di serambi mesjid Madinah.6 Fase awal ini juga disebut sebagai fase asketisme yang merupakan bibit awal tumbuhnya sufisme dalam peradaban Islam. Keadaan ini ditandai oleh munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan akhirat, sehingga perhatiannya terpusat untuk beribadah dan mengabaikan keasyikan duniawi. Fase asketisme ini setidaknya berlangsung sampai akhir abad II Hijriah, dan memasuki abad ke III sudah menampakkan adanya peralihan dari asketisme ke sufisme. Fase ini dapat disebut sebagai fase kedua, yang ditandai oleh (antara lain) pergantian sebutan zahid menjadi sufi.
Di sisi lain, pada kurun waktu ini percakapan para zahid sudah meningkat pada persoalan bagaimana jiwa yang bersih itu, apa itu moralitas dan bagaimana pembinaannya serta perbincangan masalah kerohanian lainnya. Tindak lanjut dari diskusi ini, bermunculanlah berbagai konsepsi tentang jenjang perjalanan yang harus ditempuh seorang sufi (al-maqamat) serta cir-ciri yang dimiliki oleh seorang salik (calon sufi) pada tingkatan tertentu (al-ahwal).7 Demikian juga pada periode ini sudah mulai berkembang perbincangan tentang pada derajat fana dan ittihad. Bersamaan dengan itu, tampillah para penulis tasawuf terkemuka, seperti al-Muhasibi (w.234 H), al-Harraj (w. 277H) dan al-Junaid al-Baghdadi (w. 297H), dan penulis lainnya. Secara konseptual-tekstual lahirnya sufisme barulah pada periode ini, sedangkan sebelumnya hanya berupa pengetahuan perorangan dan atau semacam langgam keberagamaan. Sejak kurun waktu itu sufisme berkembang terus ke arah penyempurnaan dan spesifikasi terminology seperti konsep intuisi, dzauq dan al-kasyf.
Kepesatan perkembangan sufisme, nampaknya memperoleh dorongan setidaknya dari tiga faktor penting, yaitu: pertama adalah karena gaya kehidupan yang glamour-profanistik dan corak kehidupan materialis-konsumeris yang diperagakan oleh sebagian besar penguasa negeri yang segera menular di kalangan masyarakat luas. Dari aspek ini, dorongan yang paling kuat adalah sebagai reaksi terhadap gaya murni ethis, melalui pendalaman kehidupan rohaniah-spiritual. Tokoh popular yang dapat mewakili kelompok ini dapat ditunjuk Hasan al-Bashri (w. 110H) yang mempunyai pengaruh kuat dalam kesejahteraan spiritual Islam, melalui doktrin al-zuhd, al-khauf dan al-raja’. Selain tokoh ini, juga Rabiah al-Adawiyah (w.185H) dengan ajaran populernya al-mahabbah serta Ma’ruf al-Kharki (w.200H) dengan konsepsi al-syauq sebagai ajarannya, juga adalah pelopor angkatan ini.8
Kedua, timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal terhadap radikalisme kaum Khawarij dan polaritas politik yang ditimbulkannya. Kekerasan pergulatan kekuasaan pada masa itu, menyebabkan orang-orang yang ingin mempertahankan kesalehan dalam suasana kedamaian rohaniah dan keakraban cinta sesame, terpaksa memilih sikap menjauhi kehidupan masyarakat ramai dengan menyepi dan sekaligus menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dengan pertentangan politik. Sikap yang demikian itu melahirkan ajaran ‘uzlah dimana konseptornya adalah Surri al-Saqathi (w. 253H).
Apabila dilihat dari aspek sosiologi, nampaknya kelompok ini bisa dikategorikan sebagai gerakan sempalan, satu kelompok ummat yang sengaja mengambil sikap ‘uzlah kolektif yang cenderung ekslusif dan kritis terhadap penguasa. Dilihat dari sisi motivasi ini, kecenderungan memilih kehidupan rohaniah mistis, sepertinya merupakan pelarian atau mencari kompensasi untuk memenangkan pertempuran ukhrawi di medan duniawi. Ketika di dunia yang sarat dengan tipu daya ini sudah kering dari siraman cinta kasih, mereka bangun dunia baru, realitas baru yang terbebas dari keserakahan dan kekejaman yakni dunia spiritual yang penuh dengan kecintaan dan kebijakan.
Ketiga, nampaknya adalah karena faktor kodifikasi hukum Islam (fiqh) dan perumusan ilmu kalam (teologi) yang dialektis-rasional, sehingga kurang bermotivasi ethical yang menyebabkan kehilangan nilai spiritualnya menjadi semacam wahana tiada isi, semacam bentuk tanpa jiwa. Formalitas paham keagamaan dirasakan semakin mengeringkan dan menyesakkan ruh al-din yang berakibat terputusnya komunikasi langsung dan suasana keakraban personal antara hamba dan Khaliqnya. Kondisi hukum dan teologi yang kering tanpa jiwa itu, dihadapkan pada dominannya posisi moral dalam agama, menggugah para zuhud untuk mencurahkan perhatian terhadap moralitas, sehingga memacu pergeseran asketisme kesalehan kepada sufisme.
Doktrin al-zuhud misalnya yang tadinya sebagai dorongan untuk meninggalkan ibadah semata-mata karena takut pada siksa neraka, bergeser kepada demi kecintaan dan semata-mata karena Allah, agar selalu dapat berkomunikasi dengan-Nya. Konsep tawakkal yang tadinya berkonotasi kesalehan yang etis, kemudian secara diametral dihadapkan kepada pengingkaran kehidupan duniawi-profanistik di satu pihak dan konsep sentral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang kemudian popular dengan doktrin al-hubb. Doktrin ini adalah semacam pra-ma’rifat yakni mengenal Allah secara langsung melalui pengalaman bathin. Menurut sebagian sufi (tasawuf sunni) ma’rifatullah adalah tujuan akhir dan merupakan tingkat kebahagiaan yang paripurna yang bisa dicapai manusia di dunia ini. Untuk bisa mencapai kualitas ilmu seperti itu, harus melalui proses inisiasi yang panjang dan bertingkat-tingkat dan hanya dimiliki orang-orang tertentu saja.
Dalam kurun waktu yang sama, tampil Dzu al-Nan al-Mishri (w.245H) dengan konsepsi metodologi spiritual menuju Allah, yakni al-maqamat yang secara parallel berjalan bersama al-hal yang bersifat psiko-gnostik. Sejak diterimanya secara luas konsepsi al-maqamat dan al-ahwal, perkembangan tasawuf telah sampai pada tingkat kejelasan perbedaannya dengan kesalehan asketis, baik dalam tujuan maupun ajarannya. Selain dari pada itu, sejak periode ini kelihatannya untuk menjadi seorang sufi semakin berat dan sulit, hampir sama halnya dengan kelahiran kembali seorang manusia, bahkan jauh lebih berat dari kelahiran pertama.
Karena kalau kelahiran pertama menyongsong kehidupan duniawi yang mengasyikkan, tetapi pada kelahiran kedua ini, justru melepas dan membuang kehidupan material yang menyenangkan, untuk kembali kea lam rohaniyah, pengabdian dan kecintaan serta kesatuan dengan alam malakut. Sementara itu pada abad ketiga ini juga Abu Yazid al-Busthami (w.260H) melangkah lebih maju dengan doktrin al-ittihad melalui al-fana, yakni beralih dan meleburnya sifat kemanusiaan (nasut) seseorang ke dalam sifat ilahiyah sehingga terjadi penyatuan manusia dengan Tuhan dalam al-fana. Sejak munculnya doktrin al-fana dan al-ittihad, terjadi pulalah pergeseran tujuan akhir dari sufisme. Kalau mulanya sufisme bertujuan ethis, yakni agar selalu dengan Allah sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan Allah, maka selanjutnya tujuan itu menaik lagi pada tingkat penyatuan diri dengan Tuhan. Konsep ini berangkat dari paradigm, bahwa manusia yang secara biologis adalah jenis makhluk yang mampu melakukan satu transformasi dan transendensi melalui peluncuran (mi’raj) spiritual ke alam ketuhanan.
Berbarengan dengan itu, timbul pula sikap pro-kontra terhadap konsep al-ittihad dan menjadi salah satu sumber terjadinya konflik dalam dunia pemikiran Islam, baik intern sufisme maupun dengan fuqaha dan para teolog. Dua kelompok ini secara bersama menuduh penganut sufisme al-ittihad sebagai gerakan sempalan yang telah merusak prinsip-prinsip Islam. Apabila dilihat dari sisi tasawuf sebagai ilmu, maka fase ini merupakan fase ketiga yang ditandai dengan mulainya unsur-unsur luar Islam yang berakulturasi dan bahkan sinkretis dengan sufisme. Masalah lain yang penting dicatat adalah bahwa pada kurun waktu ini juga timbul ketegangan antara kaum ortodoks Islam dan penganut sufisme awal (kesalehan asketis) di satu pihak dengan sufisme yang berpaham ittihad di pihak lain. Sufisme Orthodoks
Sebenarnya apabila ditinjau secara cermat dan menyeluruh ketegangan yang terjadi seperti yang disebutkan di atas, bukan semata mata karena masalah sufisme atau karena perbedaan sufisme atau karena perbedaan pemahaman agama, tetapi juga karena telah ditunggangi kepentingan politik, yakni kaum Sunni versus kaum Syi’i. Sebab, sejak abad ketiga hijriah sudah mulai popular sebutan sufisme ortodoks, yang dirintis oleh Harits al-Muhasibi seperti telah disebutkan terdahulu sebagai tandingan bagi sufisme popular yang didukung sepenuhnya oleh kaum Syi’ah. Tujuan sufisme ortodoks adalah ihya atsar al-salaf reaktualisasi paham salafiyah dengan mengupayakan tegaknya kembali warisan kesalehan sufi terdahulu yakni para sahabat dan generasi sesudahnya dengan tetap mempraktekkan kehidupan yang bersifat lahiriah. Dengan kata lain, bahwa gagasan al-Muhasibi itu adalah untuk merentang jembatan di atas jurang yang memisahkan Islam ortodoks dan mengawal kesucian sufisme agar tetap berada dalam wilayah Islam yang murni.9
Usaha al-Muhasibi tersebut dilanjutkan oleh para pengikutnya dengan merumuskan prinsip-prinsip sufisme ortodoks, sejak itu (abad ke III) tertengarailah sebutan Sufisme ortodoks dan nampaknya gerakan pertama dalam pembaharuan sufisme. Dalam pandangan sufisme ortodoks penyimpangan berat yang dilakukan oleh sufisme Syi’i adalah dalam aspek tauhid atau teologi. Oleh karena itu, tema sentral dari pembaharuan sufisme ini adalah rekonsiliasi antara teologi sufisme dengan teologi ortodoks yakni teologi Ahlusunnah wal jama’ah.
Salah satu rumusan teologinya ialah Islam adalah pengetahuan yang bersifat apriori dan simplisiter iman adalah pengetahuan tentang Tuhan, tentang ketuhanannya yang bertempat di qalbu (hati), ma’rifat adalah pengetahuan sejati tentang Tuhan yang berpusat dalam fuad (pusat hati), dan pengakuan tentang ke-Esaan Tuhan dengan sifat-sifatnya adalah pengetahuan tentang kesatuannya (unitasnya) yang mutlak dan tempatnya adalah sirrr (inti qalbu). Usaha rekonsiliasi yang dirintis oleh al-Muhasibi dilanjutkan oleh al-Kharraj dan al-Junaid dengan tawaran konsep-konsep tasawuf yang kompromistis antara sufisme dengan kelompok ortodoks (kaum salafiyah). Tujuan gerakan ini adalah untuk menjembatani dan bila dapat untuk mengintegrasikan antara kesadaran mistik dengan syari’at Islam. Jasa mereka yang paling berharga adalah lahirnya doktrin al-baqa (subsistensi) sebagai imbangan dan legalitas al-fana. Hasil keseluruhan dari upaya pemaduan itu, terminology sufisme membuahkan pasangan-pasangan kategori dengan target merekonsiliasi kesadaran mistis dengan syariat yang legal sebagai suatu lembaga.
Gerakan sufisme ortodoks mencapai puncaknya pada abad lima hijriah melalui tokoh monumental al-Ghazali (w.503H). gerakan ini terutama bertujuan untuk membendung invasi berkembangnya teologi sufisme yang menurut pandangan kaum ortodoks dapat merusak sendi-sendi ketauhidan, maka al-Ghazali merumuskan suatu konsepsi yang diharapkan dapat menampung aspirasi kedua belah pihak. Kalau pada kesalehan asketis (zahid) yang awal dengan penekanannya pada motif esoteric sebagai reaksi terhadap pemahaman eksternal hukum dari kelompok rasional-intelektual, al-Ghazali menampilkan doktrin al-ma’rifat. Dia maksud dengan istilah ini adalah, pengetahuan yang diperoleh melalui penjelajahan batin atau eksperimen batin, yang secara tegas dipertentang-kan dengan pengetahuan intelektual seperti teologi dialektis. Konsepsi ini bukan menentang teologi tetapi ia menentang perumusan teologi yang dilakukan secara rasional-dialektik.10 Sufisme –Theosufi
Paparan terdahulu menunjukkan, bahwa sufisme sebagai ilmu teoritis maupun praktis telah sampai pada tingkat kematangan (fase keempat), yang ditandai dengan terpilahnya sufisme kepada dua aliran besar yaitu sufisme Sunni dan sufisme Syi’i yang disebut juga sufisme falsafi atau sufisme-theosufi.11 Sebab ternyata pada akhirnya intisari pengalaman kesufian yang menurut al-Ghazali tidak mungkin diungkapkan menerobos juga lewat konsepsi Ibn Arabi (w.638H). corak ma’rifat yang dikembangkan tokoh popular dari Murcia ini, tidak sejalan dengan konsepsi ma;rifat sebelumnya. Ia bukan saja mengungkapkan kasatuan manusia dengan Tuhan seperti halnya dengan Abu Yazid al-Bistami tetapi ia menyodorkan satu bentuk olahan esoterik yang mirip dengan filsafat. Ia berusaha mencerahkan hubungan antara fenomena alam yang pluralistic dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya. Berangkat dari pendapat sufisme bahwa yang mutlak hanya Allah, ia lalu mengatakan bahwa alam ini adalah (mazhar) dari asma dan sifat Allah, yang sebenarnya adalah zat-Nya. Yang Mutlak itu merupakan diri dalam citra keterbatasan yang empiris yang kemudian popular dengan doktrin wahdah al-wujud.12
Paham baru ini kembali menimbulkan ketegangan dan pertentangan yang lebih tajam dan meliputi segenap pemikiran Islam, karena paham ini dikategori-kan sebagai pantheisme (paham serba Tuhan) yang tidak bisa disesuaikan dengan akidah Islam. Karena konsepsinya yang dinilai sementara sufi sangat ekstrim menuduhnya sudah keluar dari Islam (kafir). Apabila dilihat dari perkembangan sufisme, maka fase ini sudah memasuki fase keempat yang ditandai masuknya unsur-unsur filsafat ke dalam sufisme, baik yang bersifat metodologis maupun yang mengambil postulat-postulat filsafat Yunani terutama neo-Platonisme.
Agaknya persoalan ini pulalah yang melatarbelakangi terutama gerakan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim pada abad kedelapan Hijriyah untuk melanjutkan usaha yang pernah dilakukan al-Ghazali. Ibn Taymiyah juga mengakui validitas metode eksperimen batin sufisme (ma’rifat), tetapi kualitas keabsahan itu baru relevan dengan syari’at.13 Rumusan ini secara tegas menolak doktrin monism (wahdah al-wujud) Ibn ‘Arabi dan sekaligus juga menolak berbagai praktek ritual sufisme. Demikianlah telah terlihat bahwa masa kejayaan sufisme cukup lama dan tersebar di seantero dunia Islam. Namun memasuki abad kedelapan Hijriyah nampaknya sufisme telah memasuki masa kemandegan. Karena sejak masa itu tidak ada lagi konseo-konsep sufisme yang baru dan orisinil. Yang berjalan terus hanyalah sekedar ulasan-ulasan terhadap karya lama. Praktek pengamalan sufisme berjalan semarak tetapi lebih didominasi tarekat sebagai lembaga sufisme dan lebih menampakkan aspek ritusnya, bukan pada aspek substansinya. Neo-Sufisme
Apa yang ingin dicoba ungkapkan dari sufisme terdahulu adalah bahwa sufisme secara tegas menempatkan penghayatan keagamaan yang paling benar pada pendekatan esoterik, pendekatan batiniyah. Dampak dari pendekatan esoterik ini adalah timbulnya kepincangan dalam aktualisasi nilai-nilai Islam, karena lebih mengutamakan makna batiniyahnya saja atau ketentuan yang tersirat saja dan sangat kurang memperhatikan aspek lahiriyah formalnya. Oleh karena itu adalah wajar apabila kemudian dalam penampilannya, kaum sufi tidak tertarik untuk memikirkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, bahkan terkesan mengarah ke privatisasi agama. Di sisi lain, terdapat kelompok muslim yang mengutamakan aspek-aspek formal-lahiriyah ajaran agama melalui pendekatan eksoteris-rasional. Mereka lebih menitik-beratkan perhatian pada segi-segi syariah, sehingga kelompok ini disebut kaum lahiri. Seperti disebut terdahulu, bahwa dalam sejarah pemikiran Islam pernah terjadi polemik panjang yang menimbulkan ketegangan antara dua kubu yang berbeda orientasi penghayatan keagamaan.14
Dalam segi penamaan, neo-sufisme adalah istilah yang baru berkembang pada abad dua puluh, yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman. Namun, sejatinya gagasan neo-sufisme dalam sejarahnya telah ada sejak abad ke delapan Hijiriyah, yaitu suatu corak tasawuf yang terintegrasi dengan syari’ah, dan adalah Ibn Taymiyyah (w.728H), sebagai pencetus gagasan yang selanjutnya diteruskan oleh muridnya Ibn Qayyim.15 Kebangkitan kembali sufisme di dunia Islam dengan sebutan neo-sufisme, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan agama sebagai penolakan kepercayaan yang berlebihan kepada sains dan teknologi yang notabene merupakan produk modernism. Modernism dinilai telah gagal memberikan kehidupan yang bermakna bagi manusia, karenanya upaya kembali ke agama dianggap sebagai solusi paling tepat sebagai jalan pemaknaan terhadap kehidupan secara universal.
DAFTAR PUSTAKA
- Al-Qur’an al-Karim
- Aboebakar Atjeh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf, Kelantan Malaysia: Pustaka Aman Press, 1977 .
- Abi Bakr Muhammad Ishaq al-Kalabadzi, Al-Tasawwuf li al- Mazhab Ahl al-Tasawwuf, Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, Beirut Libanon, 1993.
- A.J. Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, terj: Bambang Herawan, Jakarta: Mizan, 1991.
- Carl W. Ernst, Shambhala Guide to Sufim, terj: Arif Anwar, Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Fazlur Rahman, Islam, penterjemah: Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Julian Baldick, Mystical Islam; An Introduction to Sufism, London: I.B. Tauris & Co Ltd , 1989
- Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Isa Abduh Ahmad Isma’il Yahya, Dr, HakIkat al-Insan, Dar al-Ma’arif, tp, tt
- Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sumber / Catatan Kaki Artikel Di Atas :
1 Isa Abduh Ahmad Isma’il Yahya, Dr, Hakikat al-Insan, Dar al-Ma’arif, tp, tt, hal. 85.
2 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 93-94.
3 Lihat al-Qur’an : QS: Al-Baqarah: 86; QS: Al-Baqarah; 115; QS; QS: Al-Maidah: 54; QS: Ali Imran: 30; Qaf: 16.
4 Carl W. Ernst, Shambhala Guide to Sufism, terj: Arif Anwar, Pustaka Sufi, Jogjakarta, 2003, hal. 153.
5 Aboebakar Atjeh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf, (Kelantan Malaysia: Pustaka Aman Press, 1977), hal. 67-78.
6 Abi Bakr Muhammad Ishaq al-Kalabadzi, Al-Tasawwuf li al- Mazhab Ahl al-Tasawwuf, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah,, 1993), hal. 15.
7 A.J. Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, terj: Bambang Herawan, Mizan, Jakarta, 1991, hal. 81-90.
8 Julian Baldick, Mystical Islam; An Introduction to Sufism, (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 1989,) , hal. 33.
9 Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 301.
10 Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik…, hal.304.
11 Fazlur Rahman, Islam, penterjemah: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1997), hal. 204
12 Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik…, hal.304.
13 Fazlur Rahman, Islam…, hal. 210.
14 Fazlur Rahman, Islam.., hal. 213.
15 Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik…, hal.309.